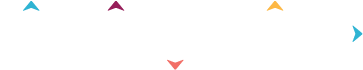Satu pagi, di ambang Ramadan yang bening, tawaran itu tiba. Sehelai surat bertulis rasmi, tertera cap DBKL dan jemputan dari WHO serta Bloomberg—Sarah dipilih menjadi delegasi Kuala Lumpur ke Paris dalam program Healthy Cities. Aku melihat raut wajahnya yang bercampur antara keterujaan dan kegusaran. Paris, kota yang menjadi lambang tamadun dan kemodenan, sedang memanggil namanya. Tetapi di sebalik panggilan itu, ada tanggungjawab yang masih membayangi—anak-anak yang perlu ditinggalkan, sekolah yang masih berjalan, Ramadan yang menanti dengan segala keberkatannya.
Aku, yang mendengar kisah ini, merasakan desir halus dalam dada. Paris. Nama itu sendiri membawa makna, bagai sebutir permata yang berkilau dalam sejarah. Kaca-kaca tingkap Notre-Dame, kubah Sacré-Cœur yang menyimpan seribu doa, jalanan Saint-Germain yang telah menyaksikan jejak para filsuf. Keinginan untuk mengikut serta, untuk melangkah ke kota yang selama ini hanya aku kenali lewat halaman buku, tumbuh diam-diam.
Namun, dilema membelit. Siapa yang akan menjaga anak-anak? Bagaimana dengan kos yang perlu aku tanggung sendiri? Dan adakah ini keputusan yang benar—meninggalkan rumah di bulan suci, demi sebuah perjalanan yang masih samar hikmahnya?
Kami berdua menimbang, meneka-neka takdir. Dalam resah yang mula menderas, kami tanyakan pada Baba dan Tok Ma. Dengan kasih yang tak bertepi, mereka mengangguk, menawarkan diri menjaga anak-anak sepanjang pemergian kami. Kelegaan itu datang seperti angin lembut selepas hujan—mendinginkan hati yang sekian lama ragu.
Lalu, datang pula takdir kedua. Seorang sahabat di UK menghulurkan jemputan, menawarkan perjalanan lanjut. Jika sudah sampai ke benua ini, mengapa tidak menyeberang ke Britain? Sarah, yang sekian lama mengimpikan pertemuan dengan Sheikh Atabek—tokoh yang mengajarnya Perubatan Ibn Sina—terus diam seketika, seolah-olah menghitung sesuatu dalam jiwanya. Mungkin doa-doanya selama ini sedang dijawab satu per satu.
Aku melakukan istikharah. Dalam sujud dan doa, aku mohon petunjuk, memohon agar jika perjalanan ini ditakdirkan untuk kami, maka biarlah ia dipermudahkan dari segala segi—biaya, aturan, juga hati yang lapang menerima.
Dan sungguh, Allah menjawab dengan cara yang tidak disangka.
Beberapa hari kemudian, Sarah menerima berita bahawa Datuk Bandar KL sendiri telah menandatangani surat pengesahan. Tiket penerbangan diberikan. Laluan ke Paris kini terbuka. Aku meneliti harga tiket untuk penerbangan yang sama—Emirates, transit di Dubai, bertolak sekitar 17 haribulan dan kembali sebelum Ramadan berakhir. Ketika menekan butang carian, ada debar yang mengiringi. Tapi saat harga muncul di skrin, aku hampir tidak percaya. Setelah menebus miles points, kosnya hanya sekitar RM2,100—dan aku dapat memilih tempat duduk bersebelahan dengan Sarah.
Aku diam lama, merenung skrin yang bersinar di hadapan. Apakah ini bukan satu tanda? Apakah ini bukan jawapan kepada istikharahku?
Paris kini menunggu. Manchester juga memanggil.
Dan begitulah kisah bagaimana kami akhirnya berangkat, menjadi musafir di kota-kota ilmu, di bulan yang penuh rahmat. Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang berbeza—bukan sekadar kerana sahur di bawah langit Eropah, tetapi kerana ia adalah sebuah perjalanan yang ditenun dengan doa dan takdir yang telah lama tersurat.